
Kita adalah sepasang merpati dalam cerita yang ditulis oleh pengarang tua itu. Pengarang yang hidupnya selalu sepi dan selalu dilanda kesedihan yang kita tahu sejak cerita tentang kita mulai ditulis. Kita tak tahu pasti apa yang menyebabkan ia kesepian dan selalu merasa sedih dalam hidupnya. Mungkin kesedihannya disebabkan oleh foto yang kini tergeletak di atas meja kerjanya. Foto seorang wanita berambut ombak yang tengah tersenyum, menggunakan gaun putih seperti dalam pesta ulang tahun dan membawa bunga mawar. Mungkin itu foto lama, karena sudah sedikit usang dan bingkainya mulai berdebu…
Setiap pagi, ketika pengarang tua itu terbangun dari tidurnya, ia akan menghampiri foto itu. Ia akan memandangi foto itu lekat-lekat dari ujung rambutnya, kemudian akan berhenti pada senyumnya, hingga akhirnya pengarang kita akan tersenyum, atau meneteskan air mata. Sesekali, ia juga akan memeluk foto itu seperti seorang ayah memeluk anaknya, atau lebih tepatnya seorang suami memeluk istrinya. Begitu juga ketika siang hari sebelum ia makan, sebelum mulai menulis, ataupun malam sebelum tidur, ia selalu memandangi foto itu dengan mimik yang hampir sama: tersenyum, atau meneteskan air mata.
Kita tak pernah mengerti benar, bagaimana sebuah foto bisa membuat seseorang merasa kesepian ataupun bersedih. Hingga suatu hari, diam-diam kita menyimpulkan bahwa wanita di foto itu adalah istrinya.
Merasa iba dengan nasib pengarang tua itu, kita berniat untuk menghiburnya agar ia tak kesepian ataupun bersedih lagi. Lalu kita membayangkan diri kita sebagai sesosok makhluk yang jenaka seperti badut misalnya, dengan hidung besar berwarna merah, dan muka yang menggemaskan. Lalu di depannya kita akan membuat sebuah pertunjukan sirkus yang tidak terlalu serius tetapi jenaka. Dan kita membayangkannya ketika pengarang tua itu tertidur pulas setelah sebelumnya ia menangis karena foto wanita yang kita simpulkan sebagai istrinya. Aku yang memulai mengatakan ide itu kepadamu sebelum kita membayangkan hal itu bersama-sama.
Namun, akhirnya kita sadar bahwa kita masih terkurung dalam cerita yang dibuat oleh pengarang tua itu. Lalu kita mengutuki diri kita sendiri karena tidak bisa membantu pengarang tua itu, dan kenapa pula pengarang itu menciptakan kita sebagai sepasang merpati dan bukan sepasang badut yang jenaka, atau sepasang badut pemain sirkus. Andaikan pengarang itu bisa secepatnya menyelesaikan kisah kita, mungkin ia akan menulis kita dalam tokoh cerita lain, dan kita berharap itu adalah cerita yang jenaka, dengan tokoh kita sebagai sepasang badut. Meskipun peluang ia membuat tokoh ceritanya sebagai badut adalah seperseribu bahkan seperjuta sekian, tapi apa salahnya jika kita berharap bahwa kemustahilan itu tak pernah ada dan yang ada hanyalah kepastian bahwa tokoh cerita yang akan ia buat setelah menyelesaikan cerita kita adalah badut yang lucu.
***
Pada suatu pagi, di hari minggu yang cerah, untuk pertama kalinya kita melihat pengarang tua itu tertawa setelah ia berbicara dengan seseorang lewat telepon. Kita berpikir ia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dari seseorang yang meneleponnya, dan hal itu membuat ia melupakan kesedihannya.
“Sayang, hari ini tulisanku dimuat di media nasional yang aku impikan dari sejak awal aku mulai menulis. Dan siang nanti aku akan dikirimi bukti terbitnya, dan seminggu lagi tukang pos akan datang mengetuk pintu rumah kita membawa honor tulisanku. Aku bahagia sekali hari ini sayangku.”
Kita melihat ia mengelus foto istrinya, tawanya hilang lalu berganti air mata.
“Andai saja kau ada di sini bersamaku, pasti kau akan ikut bahagia. Kau akan meloncat-loncat seperti anak kecil, lalu kau akan mengajakku keluar untuk jalan-jalan dan pasti aku akan mentraktirmu makan di restoran impianmu.”
Pengarang tua itu kembali tenggelam dalam kesedihannya. Kita ikut terseret dalam kesedihan, dan aku melihat matamu berkaca-kaca yang membuat mataku juga ikut berkaca-kaca. Betapa kesedihan selalu berteman air mata.
Jam sebelas limabelas, seseorang mengetuk pintu rumahnya, dan ia cepat-cepat menghapus air matanya degan lengan bajunya, lalu bergegas mendekati pintu rumahnya. Di depan pintu ia mendapati seorang tukang pos telah berdiri dan menyodorkan sebuah koran nasional yang memuat tulisannya. Setelah menemukan halaman yang memuat tulisannya, dan menghempaskan lembaran koran lainnya yang ia anggap tidak penting, ia kembali mendekati foto istrinya.
“Lihat, ini dia korannya! Aku sudah menerimanya. Aku bahagia. Kau juga harus ikut bahagia di sana melihatku bahagia. Kau juga harus ikut tertawa seperti aku hari ini.”
Ia terus saja berkata dengan nada yang menggebu-gebu dan penuh kegirangan walaupun foto itu tak pernah mengucapkan kata “selamat” kepadanya, hingga akhirnya ia kelelahan dan tertidur di atas meja menindih koran yang memuat tulisannya.
***
Satu minggu kemudian, ketika pengarang tua itu baru selesai makan dan memandangi foto istrinya, seseorang kembali mengetuk pintu rumahnya yang ternyata adalah tukang pos. Tukang pos itu menyodorkan sebuah amplop padanya dan ketika ia membukanya, amplop itu berisi sejumlah uang dan sepucuk surat pengantar untuk honor tulisannya.
Sore harinya, ia pergi meninggalkan cerita tentang kita sepasang merpati dan foto yang biasa ia pandangi dengan membawa isi amplop yang ia terima dari tukang pos, kecuali surat pengantarnya yang ia biarkan tergeletak di lantai. Kita tak pernah tahu ke mana pengarang tua itu pergi sore itu. Dan kita hanya tahu ia kembali tengah malam dengan langkah sempoyongan sambil meracau tidak karuan.
Ia menendang kursi, kaleng bekas makanan ringan, botol-botol bekas air mineral, dan meja kerjanya, hingga foto istrinya terjatuh dan kacanya pecah setelah menghantam lantai. Lalu ia melemparkan koran yang memuat tulisannya ke lantai dan menginjaknya dan ia memuntahkan isi perutnya di koran itu. Ia tergeletak, lalu berguling-guling di atas muntahannya. Kita begitu waswas kalau-kalau pengarang tua itu melemparkan tulisan tentang kita yang ada di atas meja kerjanya lalu menginjak-injaknya sebagaimana yang ia lakukan pada koran yang memuat tulisannya. Tapi untungnya ia tidak melakukannya, dan kita merasa bersyukur.
Esok paginya, setelah ia sadar dan mendapati foto istrinya tergeletak di lantai dengan bingkai yang berantakan, ia mencabut foto itu dari bingkainya lalu mendekapnya erat-erat dengan tanpa henti air matanya terus menetes. Dan kesedihannya semakin menjadi-jadi ketika ia mendapati koran yang memuat tulisannya telah kotor dan rusak oleh muntahannya sendiri.
Kita hanya menjadi penonton dan kembali ikut tenggelam dalam kesedihan. Kita mengutuki kesedihan-kesedihan itu sebagai sesuatu yang lebih menyakitkan dari kematian. Dan dalam kesedihan itu, kita berharap pengarang tua itu segera menyelesaikan cerita tentang kita, sepasang merpati dan kembali menulis cerita yang baru dengan tokoh sepasang badut yang jenaka.
***
Kadang-kadang sesuatu yang kita inginkan bisa saja menjadi kenyataan. Terbukti, di suatu pagi yang mendung setelah sekian lama ia tenggelam dalam kesedihan karena selembar foto, pengarang tua itu kembali menulis dan melanjutkan cerita tentang kita. Harapan kita agar penulis tua itu menulis cerita yang baru dengan tokoh sepasang badut yang jenaka sedikit demi sedikit akan menuju pada kenyataan. Walaupun apa yang kita harapkan belum tentu menjadi kenyataan.
Kita selalu berharap sesuatu yang terbaik untuk pengarang tua itu, tetapi kita tak pernah berpikir tentang nasib kita dalam cerita yang sedang ditulisnya. Pengarang tua itu menceritakan kau mati ditembak oleh seorang pemburu saat kita sedang asyik bertengger di sebuah pohon kamboja sambil bercakap-cakap tentang masa depan yang bahagia. Jantungmu pecah setelah tertembus isi senapan, dan tubuhmu meluncur ke tanah. Aku terbang menyusul tubuhmu yang meluncur tanpa kendali. Aku tak tahu harus melakukan apa saat itu. Menerbangkanmu ke tempat yang jauh dan mengobati lukamu sambil berharap kau hidup lagi, menyerahkan diri pada pemburu itu agar ditembak dan segera menyusulmu, atau melawan pemburu itu dengan segenap tenagaku? Tetapi cerita berkehendak lain. Isi kepala pengarang tua itu berbeda dengan isi kepalaku. Dia malah menceritakan aku menangis tersedu-sedu di samping tubuhmu yang tak bernyawa tanpa melakukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar menangis. Saat pemburu itu mendekat, ia malah menceritakan aku terbang menghindari sang pemburu. Betapa bodohnya pengarang yang selalu bersedih karena selembar foto itu. Kenapa ia tidak menceritakan kalau aku mati bersamamu ditembak pemburu itu.
Setelah kematianmu, pengarang tua itu menceritakan diriku pergi ke tengah hutan yang sepi dan aku tinggal di sebuah pohon yang jauh di tengah hutan yang tak bisa dijamah oleh para pemburu. Di sana aku semakin tenggelam dalam kesedihan dan menyesal telah meninggalkanmu dan membiarkan pemburu itu melumat habis tubuhmu menjadi santapan yang enak baginya. Sungguh pengarang yang bodoh.
Dan parahnya, pengarang tua itu malah meninggalkan cerita tentangku begitu saja. Ia berubah menjadi pemurung dan tubuhnya semakin ceking. Kemudian disusul dengan batuk yang seirama gonggongan anjing, dan ia menghabiskan hari-harinya di atas tempat tidur.
Hingga akhirnya pengarang tua itu tak pernah beranjak lagi dari tempat tidurnya, yang kemudian disusul dengan bau busuk yang menguar di seluruh ruangan. Suatu sore orang-orang masuk ke kamar itu setelah bersusah-payah mendobrak pintu dan mendapati tubuh ceking pengarang tua itu telah dimakan ulat.
Sepeninggal pengarang tua itu, aku benar-benar kesepian dan selalu berharap ada seseorang yang menemukan cerita ini dan membebaskan aku dari kesedihan. Karena setelah kematian pengarang tua itu, tidak ada seorang pun yang datang ke rumah ini, selain seekor anjing borok yang selalu berteduh ketika hujan.
Suatu hari dalam keputusasaan, tiba-tiba tebersit dalam pikiranku bahwa kisah kita adalah kisah hidup pengarang tua itu yang ditulisnya dengan tokoh sepasang merpati.
(*)






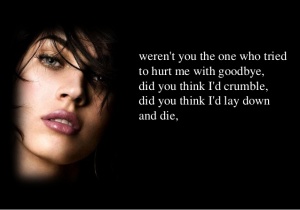


Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.